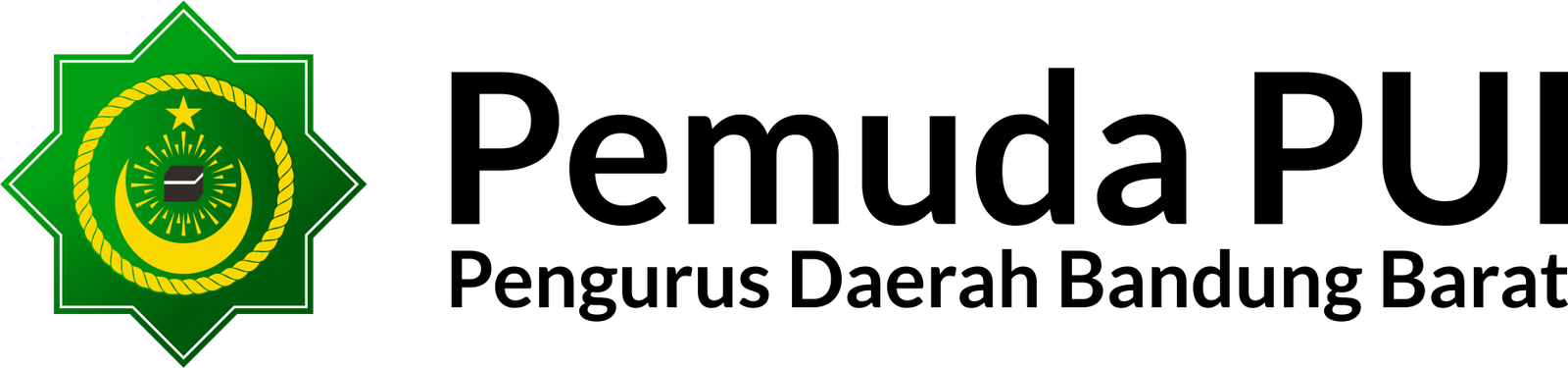Oleh: Ahmad Ghiffari Zain, S.H (Kabid Kebijakan Publik Pemuda PUI Bandung Barat)
Amnesti dan abolisi merupakan dua instrumen hukum yang secara konstitusional diberikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk prerogatif dalam sistem presidensial. Meskipun keduanya sering dianggap serupa karena berfungsi untuk menghapuskan akibat hukum dari tindak pidana, namun secara teoritis dan praktis, amnesti dan abolisi memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme dan tujuannya. Konteks aktual mengenai kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh-tokoh seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menggugah diskursus akademik dan politik tentang keabsahan, urgensi, serta konsekuensi dari kewenangan luar biasa ini.
Secara yuridis, amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan kata lain, meskipun Presiden memiliki hak prerogatif, mekanisme pemberian amnesti dan abolisi tidak dilakukan secara sepihak. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang dijunjung tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam teori hukum pidana, amnesti adalah tindakan yang menghentikan seluruh proses hukum terhadap suatu tindak pidana tertentu, baik yang sedang berjalan maupun yang belum diputus. Sementara abolisi lebih berfokus pada penghentian proses hukum secara individual, biasanya atas dasar pertimbangan politis, kemanusiaan, atau stabilitas negara (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, 2008).
Penerapan amnesti di Indonesia telah memiliki preseden panjang. Salah satunya adalah amnesti kepada para eks-pemberontak DI/TII atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini menandakan bahwa amnesti kerap dijadikan instrumen rekonsiliasi nasional. Sementara itu, abolisi tercatat jarang digunakan dan lebih bersifat selektif serta kasuistik.
Ketika wacana pemberian amnesti kepada Thomas Lembong, seorang mantan menteri ekonomi era Presiden Jokowi yang dikenal sebagai pendukung reformasi pasar dan globalisasi, mencuat, banyak pihak mempertanyakan substansi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Begitu pula dengan Hasto Kristiyanto, figur sentral di PDIP, yang sebelumnya terseret dalam pusaran kasus penghilangan barang bukti dan intervensi dalam penyidikan kasus pemilu 2024. Meskipun hingga kini belum ada proses peradilan yang inkrah terhadap keduanya, namun pemberian amnesti ataupun abolisi menjadi sinyal politis yang kuat.
Dalam konteks ini, Prabowo sebagai Presiden berpotensi menggunakan wewenangnya untuk menghapuskan proses hukum terhadap dua tokoh tersebut. Motifnya bisa bersifat strategis, terutama untuk menjaga stabilitas politik nasional dan menjalin rekonsiliasi pasca-pemilu yang berlangsung panas dan penuh polarisasi. Namun di sisi lain, tindakan ini mengandung risiko politisasi kewenangan hukum Presiden.
Secara normatif, langkah Prabowo dapat dibenarkan secara hukum apabila disertai dengan pertimbangan DPR, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, secara etik dan politik, tindakan ini akan diuji melalui opini publik dan pengawasan lembaga independen, termasuk Komnas HAM dan KPK.
Kasus ini juga mengingatkan pada polemik amnesti terhadap Baiq Nuril pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun berbeda konteks, reaksi publik terhadap pengampunan hukum menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap keadilan substantif. Jika amnesti digunakan untuk kepentingan elit politik dan bukan untuk keadilan publik, maka kredibilitas institusi hukum akan semakin tergerus (Muladi, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2005).
Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden tidak dapat dilepaskan dari implikasi yang serius, baik dari segi hukum maupun politik. Dari sisi hukum, amnesti dan abolisi harus ditafsirkan sebagai pengecualian dari prinsip equality before the law. Oleh karena itu, penggunaannya tidak boleh menjadi praktik rutin atau berbasis balas jasa politik. Bila dilakukan secara tidak proporsional, maka akan melanggar prinsip rule of law sebagaimana dijelaskan oleh Dicey (1885), yakni bahwa tidak seorang pun boleh kebal hukum dan bahwa hukum harus berlaku secara umum.
Secara politik, keputusan ini dapat memperkuat atau merusak legitimasi kekuasaan Presiden. Jika masyarakat menilai bahwa amnesti atau abolisi tersebut merupakan bentuk barter kekuasaan atau kooptasi lembaga hukum, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi akan merosot. Ini sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi pasca-reformasi. Menurut Guillermo O’Donnell (1998), negara demokratis tidak hanya membutuhkan pemilu yang bebas, tetapi juga “accountability institutions” yang efektif. Dalam konteks Indonesia, hal ini melibatkan KPK, Kejaksaan, MA, dan DPR.
Di sisi lain, dalam perspektif hukum tata negara, pemberian amnesti dan abolisi memerlukan pertimbangan yang bersifat state-oriented, bukan individual gain. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala partai atau kepala koalisi. Oleh karena itu, segala keputusan hukum yang diambil harus berdasar pada raison d’État, bukan political bargaining (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 2006).
Penggunaan amnesti dan abolisi untuk tujuan stabilitas politik perlu dikritisi karena dapat membuka celah abuse of power. Dalam praktiknya, tindakan tersebut bisa menjadi bentuk impunitas terselubung bagi elite politik. Hal ini telah menjadi kekhawatiran global dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di negara-negara transisi demokrasi. Menurut David S. Law (2010), penyalahgunaan kewenangan hukum oleh kepala negara kerap menjadi indikasi awal kerapuhan konstitusional (constitutional backsliding).
Oleh karena itu, diperlukan desain kelembagaan yang mampu mengontrol keputusan-keputusan eksekutif yang berdampak hukum tinggi. DPR sebagai lembaga pemberi pertimbangan seharusnya tidak menjadi rubber stamp, melainkan mitra kritis dalam menjaga integritas proses hukum. Bila tidak, maka praktik ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan terhadap hukum dan memperlebar jarak antara elite dan rakyat.
Masyarakat sipil, termasuk akademisi dan media, juga memiliki peran penting dalam memastikan agar kebijakan amnesti dan abolisi tidak digunakan sebagai instrumen impunitas. Melalui forum publik, diskursus hukum harus diarahkan untuk menguji rasionalitas, urgensi, dan proporsionalitas dari kebijakan tersebut
Amnesti dan abolisi merupakan instrumen hukum yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang dimiliki Presiden dalam memberikan keduanya bersifat konstitusional, namun tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip hukum yang adil, akuntabel, dan proporsional. Studi kasus tentang kemungkinan pemberian amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi cerminan nyata bagaimana instrumen hukum dapat berbenturan dengan kepentingan politik.
Pemberian amnesti dan abolisi dalam konteks ini harus dilihat lebih dari sekadar kebijakan hukum: ia adalah ujian terhadap komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan demokrasi. Oleh sebab itu, segala tindakan Presiden harus dapat diuji secara hukum dan etika publik, untuk memastikan bahwa Indonesia tidak kembali tergelincir ke dalam praktik hukum yang elitis dan transaksional.
Referensi
Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1885.
Law, David S. “Constitutional Archetypes.” Texas Law Review 87, no. 3 (2010): 517–582.
Muladi. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.
O’Donnell, Guillermo. “Horizontal Accountability in New Democracies.” Journal of Democracy 9, no. 3 (1998): 112–126.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.