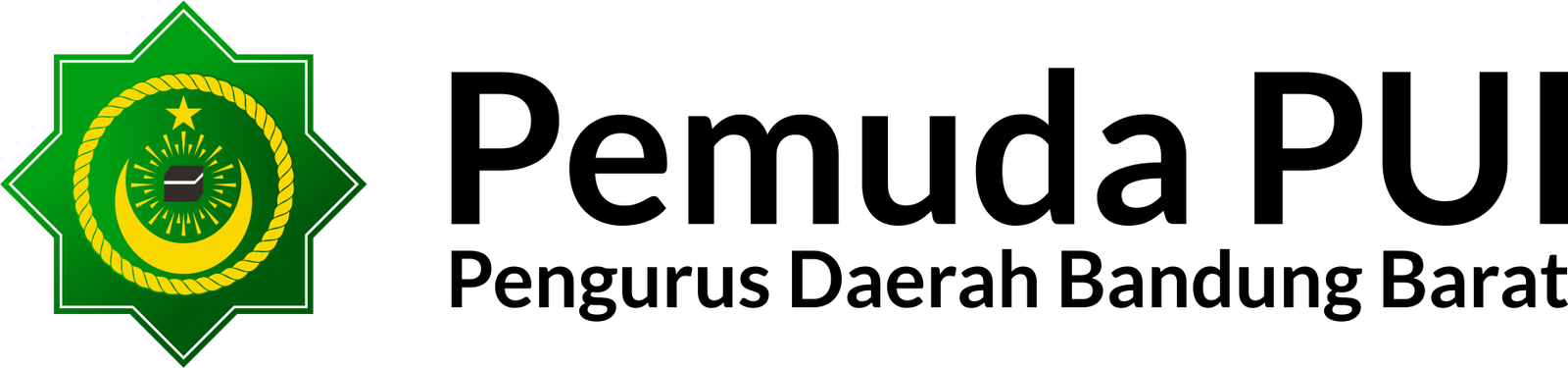Oleh : Ahmad Ghiffari Zain, S.H. (Ketua Bidang Kebijakan Publik Pemuda PUI Kabupaten Bandung Barat)
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang bergulir di parlemen seharusnya menjadi tonggak penting dalam memperbaharui sistem peradilan pidana nasional. Sebagai produk hukum warisan Orde Baru, KUHAP 1981 (UU No. 8 Tahun 1981) lahir di tengah paradigma kekuasaan yang otoriter, ketika perlindungan terhadap hak asasi manusia belum mendapat tempat dalam arsitektur hukum Indonesia. Dalam konteks ini, pembaruan KUHAP harusnya mengarah pada penguatan nilai-nilai konstitusional, perimbangan kekuasaan antar penegak hukum, serta jaminan perlindungan hak individu. Namun, justru sebaliknya, RUU KUHAP memunculkan kecenderungan penguatan otoritarianisme legal melalui perluasan kewenangan aparat tanpa mekanisme pengawasan yang kuat.
Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka supremasi konstitusi. UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan hukum yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 28A–28J. Dalam hal ini, setiap bentuk pembatasan hak warga negara oleh negara harus tunduk pada prinsip due process of law, yakni prosedur hukum yang adil, terbuka, dan diawasi secara ketat oleh kekuasaan yudisial (Asshiddiqie 2022). Namun RUU KUHAP justru memperlihatkan penyimpangan dari prinsip ini, salah satunya dalam ketentuan yang memperpanjang masa penahanan tersangka hingga 120 hari dalam tahap penyidikan. Ketentuan ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik.
Konsep due process of law merupakan prinsip yang lahir dari tradisi hukum konstitusional Anglo-Saxon dan telah diadopsi dalam sistem hukum negara-negara kontinental. A.V. Dicey menyebutkan bahwa negara hukum hanya tegak bila tindakan pejabat negara terhadap warga dapat diawasi secara yudisial (Dicey 1915). E.C.S. Wade menambahkan bahwa prosedur hukum bukan hanya legal secara formal, tetapi juga harus adil secara substansial (Wade 1982). Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah mempertegas dalam Putusan No. 55/PUU-VIII/2010 bahwa pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan adalah bagian dari prinsip konstitusional checks and balances. Ketika RUU KUHAP memberi ruang bagi penyidik untuk menuntut, maka yang terjadi adalah peleburan kekuasaan yang mengancam prinsip keadilan prosedural.
Dari sudut pandang hukum administrasi negara, RUU KUHAP juga menyimpan persoalan mendasar, terutama dalam hal diskresi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Diskresi administratif merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat untuk memilih tindakan hukum tertentu ketika undang-undang tidak memberikan satu-satunya jalan. Namun, menurut Philipus M. Hadjon, diskresi harus dibatasi oleh hukum, diawasi secara yudisial, dan dilakukan secara proporsional (Hadjon 2008). Dalam RUU KUHAP, diskresi penyidik dalam menahan, menggeledah, dan menyadap seringkali tidak dibarengi dengan pembatasan norma yang ketat. Bahkan alasan penahanan seperti ‘menimbulkan keresahan masyarakat’ bersifat sangat subjektif dan membuka ruang arbitrer.
Masalahnya tidak hanya pada luasnya diskresi, tetapi juga pada lemahnya mekanisme kontrol. Praperadilan, yang dalam KUHAP lama menjadi mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat, justru dipersempit cakupannya dalam RUU ini. Padahal, prinsip rechtsbescherming dalam hukum administrasi modern menuntut agar warga negara mendapat perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-wenang. Tanpa mekanisme kontrol eksternal, diskresi berpotensi menjadi bentuk legalisasi tindakan koersif yang tidak sah secara moral dan prinsipil.
Komnas HAM dalam kajian tahun 2023 menunjukkan bahwa pasal-pasal RUU KUHAP yang membolehkan penggeledahan dan penyadapan tanpa izin pengadilan bertentangan dengan prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 (Komnas HAM 2023). Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi penyusunan hukum pidana.
Dalam sistem demokrasi, hukum acara pidana harus mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga. Prof. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukum acara bukan hanya perangkat teknis penegakan hukum, tetapi juga perisai konstitusional terhadap potensi penyimpangan kekuasaan (Arief 2021). Dalam pandangan serupa, Prof. Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa “RUU KUHAP bukan hanya bermasalah dari sisi pasalnya, tetapi juga logika berpikir yang mendasarinya, yakni melihat warga negara bukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, tetapi sebagai objek penindakan” (Mochtar 2023).
Dari perspektif teori administrasi klasik seperti Herbert A. Simon dan Dwight Waldo, pendekatan RUU KUHAP mencerminkan model birokrasi tradisional yang hirarkis, otoritatif, dan minim partisipasi publik (Simon 1947). Padahal paradigma administrasi publik kontemporer mengarah pada new public governance yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis akuntabilitas moral. RUU KUHAP, alih-alih mencerminkan paradigma ini, justru memberi sinyal kembalinya pendekatan kekuasaan legal formalistik yang mengabaikan legitimasi substantif.
Hal yang tak kalah problematis adalah keterlibatan lembaga non-yudisial seperti TNI dan lembaga ad hoc lainnya dalam proses penyidikan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang lembaga negara harus jelas sumbernya, apakah berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat. Pemberian kewenangan kepada aktor non-yudisial tanpa pengaturan yang rigid dan akuntabel melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) dan berisiko menciptakan dualisme hukum.
Perbandingan dengan praktik negara lain juga menunjukkan bahwa tren hukum acara pidana modern bergerak ke arah perlindungan hak individu. Di Jerman dan Belanda misalnya, tidak ada tindakan penyidikan yang boleh dilakukan tanpa izin pengadilan, bahkan dalam kasus darurat sekalipun. Sistem ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak privat serta supremasi kekuasaan yudisial atas kekuasaan administratif.
Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum acara pidana semestinya mengarah ke reformasi total yang berpihak pada hak warga negara, bukan melanggengkan kekuasaan aparat. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, “Hukum acara pidana bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan cerminan dari karakter negara terhadap rakyatnya—apakah negara menjunjung martabat warga atau menindas dengan hukum” (Asshiddiqie 2022).
Oleh karena itu, pembentukan RUU KUHAP harus ditinjau ulang dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori-teori hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hak asasi manusia.
Berikut beberapa poin penting yang diharapkan oleh penulis. Pertama, pembatasan wewenang penyidik harus dibuat lebih ketat, dengan mewajibkan izin pengadilan dalam setiap bentuk tindakan yang membatasi hak.
Kedua, kontrol yudisial harus diperluas, termasuk memperkuat kelembagaan praperadilan dan menambah fungsi pengawasan.
Ketiga, pendekatan berbasis HAM dan rule of law harus menjadi fondasi dari keseluruhan sistem acara pidana.
Terakhir, keterlibatan publik dan akademisi dalam proses legislasi harus dijamin, sebagai bagian dari prinsip open legal process dalam negara demokrasi modern.
RUU KUHAP bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan cermin dari ideologi hukum negara. Bila disahkan tanpa perbaikan serius, RUU ini justru akan mengembalikan Indonesia ke era represif legal, yang mengabaikan prinsip konstitusional, akuntabilitas administratif, dan martabat warga negara.
Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi. 2021. Reformasi Sistem Peradilan Pidana. Semarang: FH Undip Press.
Asshiddiqie, Jimly. 2022. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
Dicey, A. V. 1915. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan.
Hadjon, Philipus M. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Huda, Ni’matul. 2022. Hukum Tata Negara Indonesia: Karakteristik, Prinsip, dan Perkembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Komnas HAM. 2023. Kajian Kritis RUU KUHAP. Jakarta: Komnas HAM RI.
Mochtar, Zainal Arifin. 2023. “RUU KUHAP dan Pelemahan Jaminan Konstitusional.” Diskusi Akademik Fakultas Hukum UGM.
Simon, Herbert A. 1947. Administrative Behavior. New York: The Free Press.
Wade, E.C.S. 1982. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press.
Mahkamah Konstitusi RI. 2010. Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010. Jakarta: MKRI.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.